 |
| Hutan Kalimantan / Sumber Foto : perumperindo.co.id |
KilasMalang.com -- Konferensi Pihak ke-13 Perjanjian Perubahan Iklim PBB (COP-13) yang diadakan di Bali pada tahun 2007 disambut dengan optimisme di seluruh dunia untuk mengatasi krisis iklim. Melalui usulan program REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.
Program ini sangat dihargai karena caranya yang inovatif menjaga hutan tropis sekaligus mendorong ekonomi negara berkembang melalui mekanisme perdagangan karbon. Saat ini, REDD dianggap sebagai solusi yang menggabungkan pembangunan dan konservasi. Namun, dua puluh tahun kemudian, fakta lapangan menunjukkan perbedaan yang mencolok.
Ini terutama berlaku di Kalimantan, yang seharusnya menjadi pusat konservasi tropis di seluruh dunia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih memperkuat perlindungan hutan, berbagai proyek pembangunan justru mengancam keberlanjutan ekosistem setempat.
Kalimantan kini menghadapi tekanan besar akibat deforestasi, degradasi lahan gambut, serta konflik kepentingan antara konservasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Indonesia memiliki diplomasi iklim yang luar biasa di berbagai forum internasional. Komitmen yang ditetapkan oleh NDC (Nationally Determined Contribution) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional.
Komitmen ini sejalan dengan Perjanjian Paris dan menunjukkan bahwa Indonesia mengambil tanggung jawab yang serius atas masalah iklim. Namun, kemajuan di atas kertas tidak selalu tampak dalam kebijakan nasional yang diterapkan.
Salah satu bukti yang menimbulkan kekhawatiran adalah implementasi proyek Food Estate di Kalimantan Tengah, yang paradoksnya bertentangan dengan komitmen pemerintah terhadap konservasi.Untuk memastikan ketahanan pangan nasional, terutama selama pandemi COVID-19, Food Estate awalnya dimasukkan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Namun, proyek ini menimbulkan ingatan kolektif tentang kegagalan proyek lahan gambut sejuta hektare pada era Orde Baru. Dengan mengubah ribuan hektare hutan dan lahan gambut menjadi wilayah pertanian, proyek ini justru menimbulkan masalah lingkungan baru.
Tebang dan kekeringan lahan gambut mengancam habitat fauna endemik seperti orangutan, harimau, dan burung langka, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan yang berulang.
Laporan dari WALHI dan berbagai organisasi lingkungan menunjukkan bahwa konversi hutan dalam proyek Food Estate tidak dilakukan melalui analisis dampak lingkungan yang menyeluruh dan terlibat. Ini menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Tantangan struktural yang disebabkan oleh krisis iklim tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan top-down yang berfokus pada jangka pendek. Tidak hanya proyek ini menyebabkan deforestasi dan degradasi lahan, tetapi juga menghilangkan peran masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga kelestarian hutan.
Paradoks ini menunjukkan bahwa diplomasi internasional tidak sejalan dengan kehidupan lokal. Praktik kebijakan iklim Indonesia tampaknya belum menggunakan istilah intermestik, atau hubungan antara kebijakan internasional dan domestik, seperti yang digunakan dalam studi hubungan internasional.
Program REDD yang dipromosikan secara internasional seringkali mengabaikan faktor lokal, budaya, dan kelembagaan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal melihat proyek konservasi sebagai ancaman karena mereka akan kehilangan akses mereka ke tanah adat dan sumber daya alam yang menjadi sumber hidup mereka.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh CIFOR (Center for International Forestry Research), banyak komunitas lokal di Kalimantan merasa tersingkir dari proses perumusan kebijakan. Mereka tidak hanya kehilangan hak atas tanah mereka, tetapi mereka juga kehilangan budaya dan cara hidup mereka yang berasal dari hutan.
Seringkali, mereka digambarkan sebagai penghambat kemajuan atau dianggap tidak sejalan dengan agenda nasional, daripada berpartisipasi secara aktif dalam konservasi. Meskipun demikian, konservasi dapat berhasil hanya jika masyarakat lokal terlibat dalam semua proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan kebijakan.
Di Kalimantan Timur, kondisi alam menunjukkan konsekuensi nyata dari perubahan iklim. Suhu meningkat hampir 1 derajat Celsius setiap dekade, curah hujan menjadi tidak menentu, dan risiko bencana meningkat.
Kerusakan hutan menghancurkan krisis air bersih dan mengancam keseimbangan ekosistem, yang sangat penting untuk keberlanjutan di daerah tersebut. Masyarakat lokal paling terkena dampak perubahan iklim, meskipun mereka juga paling sedikit berkontribusi terhadap emisi global.
Ironi ini menunjukkan bahwa diplomasi iklim Indonesia berhasil membangun reputasi negara di mata dunia, tetapi belum mengatasi masalah utama di dalam negeri.
Menurut teori permainan dua tingkat Robert Putnam, dukungan dan legitimasi domestik sangat penting untuk keberhasilan diplomasi internasional.
Komitmen iklim hanya akan menjadi cerita kosong yang tidak bermakna jika tidak ada sinergi antara tingkat lokal dan global.
Pemerintah harus mengubah paradigma kebijakannya dari top-down teknokratis ke arah partisipatif dan kontekstual. Untuk mencapai kebijakan iklim seperti REDD dan NDC, yang mengutamakan keadilan ekologis dan mengakui hak-hak masyarakat lokal, perlu ada kerja sama.
Kepentingan domestik dan kepentingan internasional tidak dapat hanya dikendalikan oleh pusat. Keadilan iklim dapat dicapai tidak hanya melalui perjanjian dan angka, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membantu lingkungan dan orang-orang yang bergantung padanya.
Ditulis oleh : Devina Anggraeni
Ditulis oleh : Devina Anggraeni
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Malang





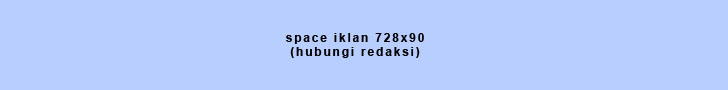



%20dan%20istri%20(1990).jpg)




